Matematika, Pelajaran Paling Pen(t)ing Sedunia
4
x 6, atau 6 x 4? Kok jadi 'never ending story'.
Sebagai
mantan anak sekolah yang tidak suka matematika, saya menyalahkan banyak hal
atas kebingungan dan mungkin kesalahan ini. Antara lain, pada suatu ketika,
saya sadar kenapa saya nggak ngeh pada teori a x b + c = n karena teori
tersebut tidak diadaptasi dengan baik ke dalam bahasa dan budaya Indonesia.
Saat itu saya baru tahu kalau n = number. Selama itu, saya nggak ngerti n
itu hasilnya berupa angka lain, atau malah huruf lain (boleh dong saya berimajinasi
sebagai penyuka ilmu non pasti).
Guru-guru
matematika yang pernah mengajari saya, mohon maaf sekali, nggak ada
yang fun. Mereka selalu merasa matematika adalah pelajaran paling penting
di muka bumi ini, melebihi pelajaran lainnya, terutama kesenian - yang sialnya
justru paling saya sukai. Pada beberapa kesempatan, saat di SMP dan lalu SMA,
pelajaran2 'tak penting' macam kesenian tadi dihilangkan dan diganti.... apa
lagi kalau bukan matematika? Sebuah kebijakan sekolah yang terlalu ambisius
menurut saya, lebih karena ingin murid-muridnya punya nilai bagus di pelajaran
yang paling penting di muka bumi tadi. (Faktanya, di kemudian hari
sebagian besar teman saya yang jago matematika, nyaris tak ada satu pun yang
jadi begawan ekonomi atau ahli kimia/ fisika.)
Saya,
pada masanya sebagai anak sekolah yang seingat saya memiliki orangtua yang
rajin bayar SPP, tentu saja merasa diperkosa dengan kondisi tersebut. Dan
lantas memutuskan tidak pernah hadir di pelajaran matematika tambahan, saat itu
menjelang ujian kelulusan sekali pun. Kebetulan, saya punya kelebihan yang
barangkali tak dimiliki oleh anak-anak berangking paling tinggi di kelas, yaitu
: menirukan tulisan tangan para orangtua, dengan nyaris tanpa cela. Jadi, kalau
mau bolos, tinggal pilih mau 'pakai' tulisan tangan siapa : kakek, ayah atau
ibu? (Oke, ini ceritanya memang jadi rada melebar ke mana-mana, tapi tetap ada
hubungannya dengan matematika tadi kok.)
Ketika
beberapa bulan menjelang ujian, dan mimpi buruk masuk sekolah dengan dijejali
matematika, tanpa ragu saya bikin surat sakit dan saya titipkan kepada salah
seorang sahabat saya, yang saya tahu dalam hatinya pengen banget punya
kenekadan seperti saya, tapi takut nilainya jeblok. Setelah beberapa hari tak
masuk, beberapa teman lain menanyakan ke sahabat saya itu, sebenarnya saya
sakit apa. Karena dikira 'tak berbahaya', sahabat saya tersebut menjawab :
"Sebenarnya nggak sakit kok, lagi ngecat kamar." Sialnya, hari itu
Ibu N, guru matematika kami menanyakan keberadaan saya yang tak pernah tampak
di ruang kelasnya. Dan spontan, R, teman saya yang mendengar saya tidak sakit
menjawab kalau saya sedang mencat kamar. (Padahal, faktanya, saya bukan cuma
mencat kamar, tapi juga bikin mural di dinding belakang rumah saya yang kala
itu cukup lebar. Jadi, logikanya, secara matematis, nggak cukuplah kalau cuma 3
hari, apalagi salah satu lukisan saya adalah seekor burung pelangi yang menurut
saya helai bulunya harus tampil sempurna : helai demi helai dengan warna yang
berbeda.)
Akhirnya,
beberapa hari kemudian saya merasa, sudah waktunya kembali ke sekolah. Dan...
dengan terpaksa bertemu dengan jam-jam setan matematika. Seperti sudah saya
duga, saya disuruh maju ke depan untuk mengerjakan sebuah teori a x c = x atau
yang lainnya, saya sama sekali tak ingat. Dan tentu saja, saya nggak bisa, lha
wong nggak tertarik babar blas, apalagi bu guru yang mungil ini orangnya kurang
manusiawi, masak muridnya nggak boleh ketawa di kelas. Padahal ketawa kan hal asasi semua manusia... Hadeeeh! Di antara
beberapa anak lain yang mengerjakan soal di papan tulis dan nggak ada yang
bisa, ada yang bener-bener gemetar, ada yang pura-pura lupa, ada pula yang diam
saja seperti saya, Bu N memilih saya untuk ditanyai.
"Nggak
bisa ya?"
Saya
menggeleng. Pasrah dan jujur.
"Mbak,
katanya minggu lalu nggak sakit ya, tapi mencat kamar?"
Wah,
kaget banget saya dengan pertanyaan yang menghujam batin tadi. "Lha kok
bisa tahu?" tanya saya dalam hati. Nggak mungkin deh sahabat saya
berkhianat. Tapi lantaran saya jujur, saya jawab saja : "Iya
Bu."
Bu
N tampak kaget dan makin kesal, mungkin dalam hatinya mikir kok ada murid
senekad ini, berani-beraninya menggantikan matematika yang digdaya dengan
mencat kamar yang sudah jelas nggak ada di kurikulum manapun. Apalagi masuk
rapot.
"Apa
menurut Mbak, pelajaran matematika itu nggak penting?" lanjut Bu N sembari
membetulkan letak kacamatanya.
"Maaf
Bu?"
"Apa
menurut Mbak matematika itu nggak penting?"
"Maaf
Bu, menurut saya nggak penting. Saya tidak bisa mengerti teori seperti ini.
Tapi kalau saya belanja, saya bisa berhitung tanpa pakai teori a x b =
z."
"....."
Dan
saya disuruh kembali ke tempat duduk.
Pada
ijazah, saya mendapat angka 5 di pelajaran matematika, meski saya tahu ada
beberapa teman yang sebenarnya lebih bloon saya. Tapi, saya mengerti
ketidaksukaan Bu Guru pada saya, seperti halnya ketidaksukaan saya pada
matematika.
Toh,
saya tetap harus merasa berterimakasih kepada matematika, yang telah memberi
saya salah satu kontribusi terbesar dalam menentukan arah hidup selanjutnya.
Antara lain kuliah di fakultas yang saya inginkan, dan tak ada pelajaran
matematikanya. Sekaligus memperjelas interest saya di bidang lain,
yang menurut saya tentu saja jauh lebih penting dari ilmu matematika. Bagi
saya, matematika sebagai science itu penting dan sudah seharusnya
dipelajari sebaik-baiknya oleh para ilmuwan terkait, begitu juga halnya
matematika sebagai ilmu akuntansi/ ekonomi -- tapi itu bukan buat saya.
Sebagai
penggemar ilmu tak pasti, ilmu pasti itu membosankan. Coba nih : kalau
dua buah garis lurus disejajarkan dan dikasih tanda '+' , maka oleh pakar
matematika mungkin saja akan dijawab dengan sebuah garis panjang yang kalau
diukur panjangnya persis dengan dua garis terpisah tadi. Tapi oleh seniman?
bisa saja dijawab dengan sebuah lingkaran, atau dua lingkaran, atau segitiga
bahkan mungkin bingkai sebuah mobil.
Tentu
saja, logika dan pengalaman saya tidak akan memberi kontribusi apa pun
kepada blunder 4 x6 = 6 x 4 tadi. Hanya saja, saya kadang masih
berharap seandainya saja para guru tidak selalu merasa pelajarannya paling
penting, mungkin jumlah orang seperti saya bisa diminimalisir. Dan andai saja,
para mentri pendidikan kita yang terhormat lebih pintar sehingga bisa
menetapkan kurikulum yang efektif, barangkali akan lebih banyak anak sekolah
yang tidak buang-buang waktu untuk mempelajari begitu banyak ilmu yang tak
mereka sukai, dan berakhir sebagai ilmu untuk mengisi TTS atau ikut kuis
(seperti yang terjadi pada saya). Percayalah, sejak kecil sekalipun sebenarnya
setiap orang sudah tahu apa yang mereka mau. Sebenarnya. Dan ini sama sekali tak
perlu pakai hitungan matematis.
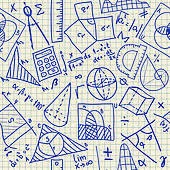




Comments
Post a Comment